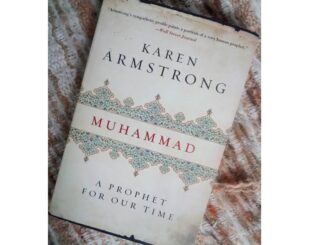Penulis: Angga Wijaya
SEORANG teman jurnalis tiba-tiba menghubungi saya. Ia tahu saya cukup paham soal pinjaman daring, maka sore itu ia bertanya tentang sistem pinjaman. Ia sedang memerlukan dana. “Mendesak,” katanya singkat.
“Apakah bisa meminjam puluhan juta rupiah, dikembalikan dalam jangka waktu empat tahun?” tanyanya.
Saya menjawab sekenanya, “Setahu saya tidak. Jangka waktu pelunasan pinjaman daring hanya antara tiga hingga enam bulan.”
Karena penasaran, saya bertanya, “Uang sebanyak itu, untuk apa?”
Entah serius atau bercanda, ia membalas, “Untuk kawin lagi…!”
Kami pun tertawa. Tawa ringan di tengah panas sore, lengkap dengan emotikon lucu. Tapi ketika obrolan selesai, kelakar itu terus menggantung di kepala saya.
Apakah “kawin lagi” — bahkan jika hanya berupa lelucon — adalah cara orang paruh baya menertawakan krisis dirinya sendiri?
Krisis yang Tidak Diakui
Usia paruh baya sering datang tanpa pemberitahuan. Tidak seperti ulang tahun ke-17 yang dirayakan, atau usia 30 yang dianggap tonggak kedewasaan. Paruh baya datang tanpa pesta. Tiba-tiba saja seseorang menyadari: rambut menipis, pinggang tak selincah dulu, anak sudah remaja, dan waktu terasa lebih pendek dari rencana.
Banyak orang tidak mengakuinya, bahkan menertawakan istilah mid-life crisis. Seolah itu hanya istilah orang Barat. Tapi siapa pun yang pernah merasakan pergeseran antara “ingin” dan “mampu”, antara “dulu” dan “sekarang”, tahu bahwa krisis itu nyata.
Teman jurnalis saya, misalnya. Ia pekerja keras, hidup dari tulisan, tapi belakangan tampak sering murung. Mungkin ia sedang lelah pada dunia yang selalu menuntut berita baru setiap jam, tapi jarang memberi waktu untuk menulis diri sendiri. Mungkin ia merasa, di usia yang tak lagi muda, idealismenya telah habis digerogoti tenggat dan utang.
Dalam tawa “ingin kawin lagi” itu, mungkin tersembunyi kerinduan akan masa muda — masa di mana cinta terasa penuh risiko dan kejutan.
Di banyak obrolan warung kopi, lelucon semacam itu bukan hal aneh. “Kawin lagi” sering muncul sebagai bahan gurauan yang “tidak berbahaya”, padahal sering menjadi simbol pencarian makna baru oleh laki-laki di usia empat puluhan.
Budaya kita, terutama di masyarakat patriarkal, memberi ruang bagi laki-laki untuk mengekspresikan krisisnya lewat simbol kekuasaan dan kejantanan: menikah lagi, membeli motor besar, atau berhubungan dengan perempuan yang lebih muda. Di baliknya, ada kegelisahan terhadap waktu yang terasa mencuri daya tarik dan relevansi.
Namun menariknya, masyarakat justru menertawakan fenomena itu, bukan memahaminya. Lelucon “kawin lagi” menjadi mekanisme pertahanan kolektif agar kita tidak perlu membicarakan hal yang lebih serius: kesepian, kehilangan makna, ketakutan akan penuaan.
Dalam dunia modern yang serba cepat, terutama bagi kelas menengah kota, mid-life crisis sering disamarkan menjadi “keinginan untuk upgrade”: mobil baru, rumah lebih besar, liburan ke Eropa, atau pasangan baru — semua menjadi cara untuk mengisi kekosongan eksistensial.
Jurnalis dan Krisis yang Sunyi
Sebagai wartawan, saya sering melihat teman-teman seprofesi berada di titik lelah yang sama. Di usia paruh baya, mereka menghadapi tekanan ganda: secara ekonomi tak lagi ringan, secara idealisme mulai goyah.
Jurnalisme, yang dulu dianggap profesi mulia, kini makin pragmatis. Orang menulis bukan lagi untuk mengguncang kekuasaan, melainkan untuk “menggugah algoritma”. Sementara honor tulisan masih sama seperti sepuluh tahun lalu.
Di tengah keadaan itu, mudah sekali bagi jurnalis merasa kehilangan arah. Ia pernah muda dan marah, pernah ingin mengubah dunia, tapi kini sibuk menulis siaran pers atau mengejar klik.
Mungkin, bagi sebagian dari mereka, mid-life crisis datang bukan hanya karena urusan biologis atau keluarga, tapi juga karena benturan antara cita-cita dan kenyataan profesi. Di antara tumpukan rilis dan rapat redaksi, seseorang bisa tiba-tiba bertanya:
“Apakah ini hidup yang aku inginkan ketika dulu memutuskan jadi wartawan?”
Di kota-kota besar Indonesia, krisis paruh baya punya wajah lain: konsumerisme. Orang berlomba membeli “simbol kebangkitan diri”: motor besar, mobil baru, gawai terbaru, gym membership, bahkan ikut workshop spiritual dengan harga jutaan.
Pasar sangat tahu cara menjual mimpi kepada orang paruh baya. Iklan tidak lagi berbicara kepada anak muda, tapi kepada mereka yang takut kehilangan masa muda. “Jangan biarkan usia menghalangi gaya hidupmu.” “Masih muda, bro!”
Namun di balik semangat itu, terselip kecemasan: takut tak diinginkan lagi, takut dianggap usang, takut hidup tanpa gairah.
Pierre Bourdieu, sosiolog Prancis, pernah menyebut fenomena ini sebagai distinction — kebutuhan manusia untuk menandai status dan identitas melalui selera konsumsi. Orang membeli bukan karena butuh, tapi karena ingin diakui.
Dan mid-life crisis adalah ladang subur bagi kapitalisme untuk menanamkan pesan: kamu bisa menebus kehilangan makna dengan belanja.
Bagaimana dengan Perempuan?
Meski istilah mid-life crisis sering dilekatkan pada laki-laki, perempuan juga mengalaminya — hanya saja, dengan cara yang lebih sunyi.
Di usia empat puluhan, banyak perempuan Indonesia harus menanggung beban ganda: karier, anak, rumah tangga, orang tua yang menua. Mereka sering tidak punya ruang untuk mengalami krisis secara terbuka.
Jika laki-laki bisa bercanda dengan “kawin lagi”, perempuan hanya bisa menatap cermin dan bergumam: “Kapan terakhir kali aku melakukan sesuatu untuk diriku sendiri?”
Mereka mungkin tidak membeli motor besar atau menggoda perempuan muda, tapi bisa tiba-tiba mengambil kursus bahasa, menanam bunga, atau mulai menulis puisi. Semua adalah cara-cara halus untuk menemukan kembali makna hidup yang sempat terbenam dalam rutinitas.
Di Bali, tempat saya tinggal, mid-life crisis sering disamarkan oleh kesibukan adat dan upacara. Orang seolah tak sempat merasa hampa karena selalu ada piodalan, metatah, atau ngaben.
Namun di sela-sela sesajen dan dupa, banyak juga orang yang diam-diam merasa kosong. Mereka menua bersama pura, tapi tidak selalu bersama makna.
Dalam konteks budaya Bali yang sangat komunal, kesepian kadang terasa lebih menyakitkan. Karena di tengah keramaian upacara, seseorang bisa merasa sangat sendirian.
Krisis paruh baya di Bali, bagi saya, adalah paradoks: hidup yang terlihat penuh warna, tapi sering kehilangan rasa.
Dari Krisis ke Kesadaran
Apakah mid-life crisis sesuatu yang buruk? Tidak selalu. Ia bisa menjadi momen kebangkitan, ketika seseorang berhenti berlari mengejar apa yang diinginkan orang lain, dan mulai mencari apa yang benar-benar penting bagi dirinya.
Banyak orang menemukan makna baru setelah krisis: mulai melukis, bertani, menulis buku, atau sekadar berdamai dengan waktu.
Krisis hanya berbahaya jika disangkal. Karena penyangkalan membuat seseorang terjebak dalam ilusi: merasa muda selamanya, merasa bisa membeli kembali waktu.
Teman jurnalis saya itu, misalnya, mungkin hanya bercanda dengan “ingin kawin lagi”. Tapi siapa tahu, itu adalah cara tubuhnya berkata: “Aku ingin mencintai sesuatu lagi, bukan hanya bertahan.”
Dan cinta yang ia maksud, mungkin bukan pada seseorang, melainkan pada dirinya sendiri yang dulu pernah penuh semangat dan keberanian.
Saya jadi teringat perkataan seorang psikiater, “Mid-life crisis hanya terasa pahit bagi mereka yang belum sempat mengenal diri sendiri.”
Mungkin benar. Karena ketika seseorang mulai memahami bahwa waktu bukan musuh, melainkan guru, maka paruh baya bukan krisis — tapi kesempatan. Kesempatan untuk menertawakan masa lalu tanpa penyesalan, dan menatap masa depan tanpa ambisi berlebih.
Dalam konteks budaya kita yang gemar menutupi luka dengan tawa, menertawakan “kawin lagi” mungkin memang bentuk paling jujur dari ketakutan. Tapi justru dari situ, manusia belajar menerima bahwa hidup tidak selalu harus bergairah agar bermakna.
Kadang, cukup dengan berdamai.
Sore itu, setelah percakapan kami berakhir, saya memandangi layar ponsel yang sunyi. Tiba-tiba saya merasa hangat — bukan karena tawa, melainkan karena kesadaran kecil: bahwa di balik setiap lelucon, selalu ada kerinduan yang tidak sempat diucapkan.nMungkin itu juga yang disebut hidup Menguji kita dengan canda, agar kita belajar menertawakan kehilangan, bukan menyesalinya. (*)
- Angga Wijaya adalah wartawan, penyair dan esais asal Bali. Telah menulis lebih dari lima belas buku, terdiri dari kumpulan puisi dan esai. Karyanya banyak terbit di media daring, termasuk Tatkala.co dan Kanalbali.id.