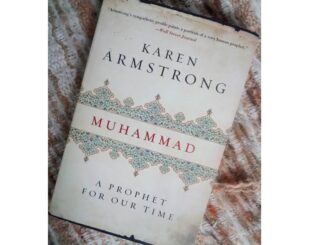Penulis: Angga Wijaya
JIKA ingin mengetahui kesehatan mental warga sebuah negara, lihatlah jalan raya yang ada.
Menonton film atau berkunjung ke luar negeri membuat kita sadar betapa tertibnya lalu lintas di negara maju. Di sana pengendara menghormati orang lain, mematuhi aturan, dan sadar bahwa keselamatan bersama lebih penting daripada ego pribadi.
Bandingkan dengan keadaan di negara kita. Jalan bagai lautan yang siap menelan siapa saja. Orang mengebut, menyalip dari arah kiri, atau membunyikan klakson panjang hanya untuk sampai lebih cepat ke tujuan.
Perilaku kita masih “barbar” sebagai masyarakat. Di jalan, sopan santun sering hilang, seakan helm hanya formalitas dan lampu lalu lintas tak lebih dari hiasan kota.
Saya kerap jatuh kasihan melihat warga yang harus menempuh jarak jauh, misalnya saat mudik, dengan sepeda motor. Tak jarang tiga hingga empat orang duduk di atas satu kendaraan, termasuk anak kecil bahkan bayi.
Risiko kecelakaan sangat tinggi. Mantan Kepala Kepolisian Daerah Bali pernah mengatakan, jumlah korban meninggal di jalan raya melebihi korban dalam sebuah perang di Suriah.
Di Bali, transportasi publik seharusnya menjadi jawaban. Namun realitasnya, jalan raya penuh sesak oleh kendaraan pribadi. Sepeda motor dan mobil begitu mudah dibeli dengan sistem cicilan, bahkan dianggap sebagai sumber pendapatan daerah.
Dampak sampingannya jarang dipikirkan, kemacetan, polusi, dan meningkatnya angka kecelakaan yang membuat jalan raya bagai “jalur tengkorak.”
Terminal kini sepi. Sopir angkutan kota dan bus antar kota dalam provinsi menunggu dengan sabar meski penumpang jarang datang. Warga lebih suka memakai kendaraan pribadi daripada naik angkutan umum.
Revitalisasi terminal perlu dilakukan. Pembangunan jalan tol yang kini dalam kajian ahli juga tidak akan menyelesaikan masalah jika transportasi publik tetap diabaikan.
Tak sedikit warga yang merindukan pengalaman naik angkutan kota di masa lalu. Bemo roda tiga atau bus Mercedes dulu menjadi tumpangan harian warga, bahkan turis asing. Kini semua hanya tinggal kenangan. Tata transportasi Bali perlu dibenahi kembali agar tidak semua beban jatuh di pundak jalan raya.
Esai tentang Jalan Raya
Dari esai pendek Pak Wicaksono, seorang pensiunan wartawan dalam akun Facebooknya “Wicaksono Wicaksono,” ia menulis bahwa jalan raya sejatinya adalah cermin besar dari kehidupan sosial kita.
Ia mengutip Erving Goffman dalam The Presentation of Self in Everyday Life untuk menjelaskan bahwa manusia di jalan tidak hanya bergerak dari satu titik ke titik lain, melainkan sedang “mempersembahkan diri.” Jalan raya adalah panggung tempat orang menampilkan siapa dirinya, dengan motor besar, mobil mewah, atau sekadar suara klakson yang mendominasi.
Wicaksono menambahkan bahwa pengendara yang menyerobot lampu merah, misalnya, sedang menunjukkan pada orang lain bahwa ia tidak mau diatur. Ia ingin dilihat sebagai orang yang berani, cepat, atau lebih unggul. Di sinilah jalan raya menjadi ruang pertunjukan ego. Apa yang kita lakukan di jalan bukan sekadar soal kendaraan, melainkan soal mentalitas.
Anthony Giddens dalam The Constitution of Society juga dirujuk oleh Wicaksono untuk membaca jalan raya. Menurut Giddens, struktur sosial selalu berinteraksi dengan agen individu. Aturan lalu lintas ada, tetapi sejauh mana ia ditaati tergantung pada pilihan tiap orang.
Ketika masyarakat secara kolektif memilih melanggar aturan, struktur itu menjadi rapuh. Jalan raya Indonesia menjadi bukti bagaimana aturan formal bisa kalah oleh kesepakatan diam-diam bahwa melanggar adalah hal biasa.
Jane Jacobs, dalam bukunya The Death and Life of Great American Cities, juga dihadirkan oleh Wicaksono. Jacobs menekankan pentingnya “mata jalan” atau kehadiran warga di ruang publik yang menciptakan rasa aman.
Namun di kota-kota kita, jalan raya justru dipenuhi ketakutan. Pejalan kaki tersisih, trotoar dipenuhi parkir motor, dan zebra cross tak lagi dihormati. Jalan seolah bukan milik semua orang, melainkan milik kendaraan bermotor.
Wicaksono bahkan mengutip Michel Foucault untuk menunjukkan bahwa jalan raya bisa dibaca sebagai ruang disiplin. Ada kamera CCTV, polisi lalu lintas, rambu, dan aturan yang seolah mengawasi tubuh kita.
Tetapi, alih-alih membentuk kepatuhan, disiplin itu justru sering diakali. Polisi bisa “damai” di tempat, kamera bisa dihindari, dan aturan bisa dilanggar bersama-sama. Foucault menulis bahwa kuasa selalu berkelindan dengan perlawanan. Di jalan raya Indonesia, kuasa aturan seringkali kalah oleh perlawanan kecil yang dilakukan secara kolektif.
Bahkan Francis Fukuyama dalam Trust The Social Virtues and the Creation of Prosperity disebut Wicaksono untuk menggarisbawahi bahwa kepercayaan sosial adalah modal utama sebuah bangsa.
Di jalan raya kita, kepercayaan itu begitu tipis. Orang enggan memberi jalan karena takut diserobot. Orang memilih menutup celah daripada memberi kesempatan. Dari sini kita bisa melihat, rendahnya tingkat kepercayaan sosial di jalan raya menjadi cerminan rendahnya kualitas kehidupan publik kita.
Kesehatan Mental
Apa yang ditulis Wicaksono memperkuat pandangan bahwa jalan raya berhubungan langsung dengan kesehatan mental masyarakat. Di tengah kemacetan, stres mudah muncul. Klakson jadi pelampiasan, makian jadi bahasa sehari-hari. Orang terbiasa marah-marah di jalan. Jika setiap hari kita menghadapi suasana seperti itu, bagaimana mungkin kesehatan mental bisa terjaga?
Bagi sebagian orang, perjalanan ke kantor adalah beban psikologis. Waktu tempuh yang lama, suara bising, polusi, dan risiko kecelakaan menambah tekanan hidup. Jalan raya yang macet adalah sumber rasa lelah sebelum bekerja. Di sinilah hubungan antara tata kota, transportasi publik, dan kesehatan mental warga menjadi nyata.
Membenahi jalan raya bukan hanya soal infrastruktur, melainkan juga soal budaya. Ketertiban lalu lintas tidak bisa dipaksa hanya dengan polisi atau kamera tilang, tetapi harus lahir dari kesadaran kolektif. Budaya antre, budaya menghormati pejalan kaki, budaya menahan ego di jalan — semua ini adalah bagian dari pembangunan mental bangsa.
Transportasi publik yang memadai adalah salah satu kunci. Jika warga lebih memilih naik kendaraan pribadi, maka jalan raya akan tetap menjadi lautan yang mengerikan. Namun jika pemerintah mampu menyediakan transportasi publik yang murah, aman, dan nyaman, warga akan punya pilihan.
Terminal akan hidup kembali, sopir angkutan kota akan kembali berfungsi, dan jalan raya akan lebih bersahabat.
Pada akhirnya, jalan raya adalah ruang publik yang tidak bisa dihindari. Kita semua bertemu di sana, entah sebagai pengemudi, penumpang, atau pejalan kaki. Jalan raya mencerminkan siapa kita sebenarnya. Jika di jalan kita kasar, egois, dan tak mau diatur, maka begitulah wajah bangsa ini.
Maka benar apa yang ditulis Pak Wicaksono, jalan raya adalah cermin buram republik. Dari cermin itu kita bisa bercermin pada diri sendiri. Apakah kita masih waras? Apakah kita masih bisa menjaga kesehatan mental di tengah lautan klakson, debu, dan emosi? Jawabannya bergantung pada sejauh mana kita berani mengubah cara kita berkendara, sekaligus cara kita hidup bersama. ( kanalbali/IST )