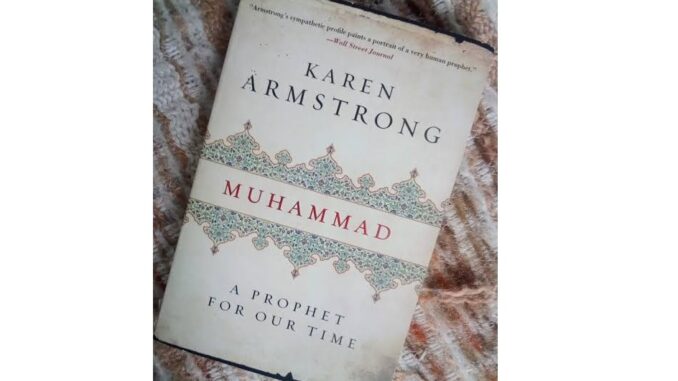
Penulis: Angga WIjaya
Umat Islam di berbagai penjuru dunia dalam suasana memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW.
Di Indonesia, perayaan itu dikenal dengan sebutan Maulid Nabi. Di sejumlah tempat, Maulid dirayakan dengan gegap gempita. Ada yang menggelar pengajian, membaca barzanji dan syair pujian, menyalakan lampu-lampu hias, sampai mengadakan lomba keagamaan.
Di Bali, terutama di kampung-kampung Muslim tua seperti Loloan di Jembrana atau Pegayaman di Buleleng, Maulid juga diwarnai tradisi unik. Anak-anak mengenakan busana terbaik, ada arak-arakan, bahkan ada yang menyebutnya mapag Maulid.
Saya masih ingat betul, ketika kecil, ibu angkat saya mengajak menonton arak-arakan itu di Loloan. Lampu-lampu minyak dinyalakan, anak-anak berjalan sambil membawa obor kecil. Di antara suara bedug dan salawat, ada rasa hangat yang sulit dilupakan. Di sanalah saya merasa, Maulid bukan sekadar ritual, melainkan juga ruang kebersamaan dan identitas.
Namun, pertanyaan penting yang patut direnungkan adalah apakah kita hanya berhenti pada perayaan lahiriah, ataukah kita juga mencoba menggali makna kelahiran Nabi Muhammad sebagai sosok yang membawa pesan universal untuk seluruh umat manusia.
Cahaya di Tengah Jahiliyah
Muhammad lahir di Mekah pada tahun 570 M, sebuah era yang dalam tradisi Islam disebut sebagai zaman jahiliyah. Saat itu, masyarakat Arab dilanda kekacauan moral, kesenjangan sosial mencolok, perang antarsuku, perbudakan merajalela, perempuan diperlakukan sebagai warga kelas dua, bahkan bayi perempuan kerap dikubur hidup-hidup.
Di tengah situasi seperti itu, Muhammad tumbuh sebagai pribadi yang jujur dan dipercaya. Ia digelari al-amin, yang terpercaya. Sebelum diangkat menjadi nabi, ia dikenal sebagai pedagang yang adil, tetangga yang baik, suami yang penuh kasih, dan sosok yang selalu merenung di Gua Hira. Dari sosok inilah lahir sebuah revolusi moral dan spiritual yang kemudian mengubah sejarah dunia.
Di dunia Barat, citra Nabi Muhammad tidak selalu positif. Sejak era Perang Salib hingga kolonialisme, ada bias panjang yang menggambarkan beliau sebagai tokoh penuh kekerasan. Inilah yang coba dibantah oleh Karen Armstrong, seorang penulis dan sejarawan agama asal Inggris.
Dalam bukunya Muhammad: A Prophet for Our Time (2006), Armstrong berusaha menampilkan Nabi Muhammad dengan pendekatan humanis dan sejarah yang lebih objektif. Ia menegaskan bahwa Islam sejak awal berdiri di atas fondasi welas asih, bukan kekerasan. Menurut Armstrong, Nabi Muhammad bukan hanya seorang nabi agama, melainkan juga reformis sosial, pemimpin moral, dan manusia yang relevan untuk zaman modern.
Armstrong menulis bahwa jika kita menilainya secara jujur, Muhammad adalah figur yang menawarkan jawaban moral atas krisis sosial yang melanda masyarakatnya, dan jawabannya tetap relevan bagi dunia kita yang juga sedang dilanda krisis.
Rahmah, Inti Pesan Nabi
Salah satu hal yang ditekankan Armstrong adalah bahwa inti dari ajaran Nabi Muhammad adalah rahmah, kasih sayang. Al-Qur’an sendiri menyebut Nabi sebagai rahmatan lil ‘alamin, rahmat bagi seluruh alam.
Spirit rahmah ini sangat relevan di Indonesia. Kita hidup dalam masyarakat majemuk dengan ratusan etnis dan agama. Prinsip welas asih Nabi sejalan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan filosofi gotong royong yang menjadi nafas bangsa. Bahkan di Bali, pesan rahmah bisa disejajarkan dengan filosofi Hindu Tat Twam Asi, aku adalah engkau. Artinya, manusia diajak untuk melihat dirinya dalam diri orang lain, menumbuhkan empati, dan menolak kekerasan.
Saya sering teringat ketika menyaksikan Maulid di kampung. Umat Hindu yang menjadi tetangga dekat, dengan senyum ringan, membantu menyiapkan kursi atau ikut mengatur jalan arak-arakan. Tak ada sekat. Di sana, rahmah bukan sekadar kata di kitab, melainkan hadir nyata dalam keseharian.
Jika pesan rahmah ini benar-benar dihidupkan, maka peringatan Maulid bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk memperkuat tali kemanusiaan lintas iman.
Nabi Muhammad tidak hanya berbicara soal ibadah ritual. Ia juga melakukan reformasi sosial yang radikal untuk zamannya. Ia menentang kesenjangan ekonomi Quraisy yang dikuasai segelintir elit dagang. Ia memperjuangkan hak-hak perempuan, menghapus praktik penguburan bayi perempuan, dan menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama hamba Allah. Ia membela kaum tertindas, membebaskan budak, dan menolak diskriminasi.
Jika kita cerminkan ke Indonesia hari ini, pesan sosial Nabi masih sangat relevan. Kita hidup di tengah ketimpangan ekonomi, di mana segelintir orang menguasai kekayaan sementara jutaan lain berjuang dengan gaji di bawah standar. Diskriminasi gender dan intoleransi agama masih terjadi.
Di titik inilah, teladan Nabi sebagai reformis sosial seharusnya menjadi inspirasi. Bahwa keimanan tidak bisa dipisahkan dari keberpihakan kepada kaum lemah. Bahwa agama bukan hanya doa dan ritual, melainkan perjuangan mewujudkan keadilan sosial.
Nabi dan Dialog Antarbudaya
Karen Armstrong juga menekankan peran Nabi Muhammad sebagai figur yang mampu membangun jembatan antarbudaya. Di Madinah, beliau memprakarsai Piagam Madinah yang menegaskan hak-hak warga non-Muslim, termasuk Yahudi, untuk hidup damai berdampingan. Piagam itu bisa dilihat sebagai salah satu dokumen awal tentang pluralisme.
Dalam konteks Indonesia yang terdiri dari ratusan suku dan agama, spirit ini sangat penting. Nabi tidak mengajarkan eksklusivisme, melainkan keterbukaan. Di Bali, kita melihat bagaimana perayaan Maulid seringkali juga dihadiri oleh tetangga Hindu, sebagai bentuk solidaritas sosial. Di beberapa desa, umat Hindu bahkan ikut membantu menyediakan perlengkapan atau konsumsi saat umat Islam merayakan Maulid. Itu adalah cermin nilai rahmah yang melampaui batas-batas identitas.
Sayangnya, perayaan Maulid seringkali lebih menekankan aspek seremonial. Lampu hias, pesta rakyat, lomba-lomba, semuanya penting sebagai ekspresi kebudayaan. Namun yang lebih penting adalah bagaimana kita memaknai ulang kelahiran Nabi sebagai momentum refleksi moral.
Armstrong menekankan bahwa Muhammad adalah nabi untuk zaman kita. Artinya, beliau bukan hanya relevan bagi umat Islam abad ke-7 di Jazirah Arab, tetapi juga bagi dunia abad ke-21 yang tengah dilanda krisis moral, konsumerisme, kesenjangan sosial, dan konflik identitas.
Pertanyaan yang selalu mengusik saya ketika menyaksikan perayaan Maulid adalah ini. Apakah kita sungguh merayakan Nabi, atau hanya merayakan diri kita sendiri dengan pesta dan gemerlap.
Ketika kita merayakan Maulid di Indonesia, kita sebenarnya sedang merayakan nilai-nilai universal, welas asih, keadilan, kesetaraan, dan solidaritas. Karen Armstrong mengingatkan bahwa Muhammad adalah figur yang harus dilihat dengan kejujuran sejarah, bukan dengan prasangka.
Di Bali, nilai welas asih Nabi bisa berdialog dengan filosofi Tat Twam Asi. Di Indonesia, pesan beliau sejalan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Di dunia, teladan Nabi bisa menjadi inspirasi untuk keluar dari lingkaran kebencian dan ketidakadilan.
Maulid bukan sekadar mengenang kelahiran seorang manusia besar, tetapi momentum untuk bertanya pada diri sendiri apakah kita sudah benar-benar meneladani rahmah yang beliau bawa. Apakah kita sudah menghidupkan keadilan sosial yang beliau perjuangkan. Atau kita justru masih terjebak pada perayaan seremonial yang hampa makna.
Nabi Muhammad, sebagaimana ditulis Armstrong, adalah sang nabi untuk zaman kita. Pertanyaannya, apakah kita siap menjadikannya teladan dalam kehidupan nyata, di tengah dunia yang semakin terpecah oleh kebencian dan ketidakadilan. (*)
*) Penulis dan jurnalis kelahiran Negara, Jembrana, Bali. Bekerja dan menetap di Kota Denpasar.





