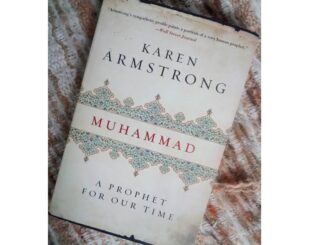Penulis: Angga Wijaya
RAKA baru tiba di kos saat malam mulai beranjak.
Di tangannya, terlihat sebungkus nasi jinggo beserta kerupuk, hendak ia makan malam ini. Berangkat kerja saat pagi dan pulang malam hari sudah beberapa tahun ini ia lakoni. Raka adalah seorang jurnalis lepas di sebuah media online di Denpasar.
Jika ditotal, gajinya tak sampai menyentuh UMR Kota Denpasar. Dalam sebulan, ia hanya bisa mengantongi pendapatan sekitar dua juta rupiah.
Untuk penghasilan tambahan, ia kerap menerima jasa penyuntingan tulisan dari sahabat dan kenalan baru yang mengenalnya lewat media sosial atau media online tempat ia menulis esai, reportase, feature, dan puisi. Hidup sederhana—untuk tidak menyebut miskin—telah ia perhitungkan secara matang.
Pilihannya menjadi jurnalis lepas dan penulis sudah sejak lama ia tentukan.
Siang tadi, saat ada waktu luang, Raka membaca sebuah artikel di akun Instagram milik anak-anak muda Bali yang dikenal kritis. Isinya tentang Denpasar yang, menurut data terbaru, disebut sebagai kota dengan standar hidup tertinggi di Indonesia.
Ia membaca komentar warganet di bawah unggahan itu. Ada yang mengiyakan, ada pula yang menyangkal. Disebutkan bahwa semua itu tergantung gaya hidup. Masih ada, kata sebagian orang, harga makanan dan tempat tinggal yang terjangkau, sesuai dengan pendapatan warga.
BACA JUGA: ‘Amongken Liangne, Amonto Sebetne’, Mindfulness Ala Bali
Raka tak ingin larut dalam perdebatan itu. Pekerjaannya sebagai jurnalis membuatnya terbiasa skeptis, tidak mudah percaya pada apa yang tampil di media. Malam harinya, ia mengecek ulang data tentang Denpasar sebagai kota dengan standar hidup tertinggi di Indonesia. Ternyata, beberapa media nasional dan lokal dalam minggu yang sama juga menulis hal serupa.
Namun Raka tidak terkejut. Ia justru bersyukur, walau dengan gaji pas-pasan, masih bisa bertahan hidup di Kota Denpasar.
Dalam keadaan sulit, ia juga pernah meminjam uang dari pinjaman daring. Ia termasuk debitur yang taat membayar utang, meskipun beberapa kali sempat meminta restrukturisasi.
Semua bisa ia atasi. Sejak 2015, Raka juga memiliki bisnis rintisan sampingan, yakni toko buku online yang ia kelola sendiri. Pemasukannya tak besar, tapi cukup. Ada saja orang yang membeli buku darinya—baik secara daring, maupun saat ia menjajakan buku secara langsung kepada kerabat, sahabat, guru, dan dosen.
Keadaan atau kondisi susah, dalam ungkapan orang Bali, sering disebut dengan kalimat “Taluh Apit Batu.”
Gara-gara Modifikasi Tangki Mobil Jadi 120 Liter, Pria di Bali Diduga Timbun BBM Bersubsidi
Makna Taluh Apit Batu
Secara harfiah, taluh berarti telur, apit berarti diapit, dan batu adalah batu. Taluh apit batu menggambarkan sebuah telur yang terjepit di antara dua batu keras. Ia rapuh, tertekan, dan nyaris tak memiliki ruang untuk bergerak. Sedikit saja salah posisi, ia akan pecah.
Dalam kebudayaan Bali, ungkapan ini digunakan untuk menggambarkan kondisi hidup yang serba terjepit, dimana tekanan datang dari dua arah atau lebih, tanpa ruang bernapas. Bisa berarti tekanan ekonomi dan sosial, tuntutan adat dan kebutuhan hidup, atau persaingan kerja dan keterbatasan peluang.
Taluh apit batu bukan sekadar kemiskinan. Ia lebih dalam dari itu. Ia adalah keadaan ketika seseorang masih berusaha bertahan, masih bekerja, masih berjuang—namun selalu berada di posisi rawan. Tidak jatuh sepenuhnya, tapi juga tidak benar-benar aman.
Ungkapan ini lahir dari masyarakat agraris Bali yang akrab dengan simbol alam. Telur adalah lambang kehidupan, potensi, dan keberlanjutan. Batu melambangkan kekuatan, tekanan, dan sesuatu yang tak mudah digeser. Ketika telur diapit batu, kehidupan berada dalam ancaman konstan.
BACA JUGA:“Nglaleng Bangke”: ‘Rebel’ ala Remaja Bali
Denpasar dan Paradoks Standar Hidup
Dalam beberapa indikator statistik terbaru Badan Pusat Statistik, Denpasar kerap disebut sebagai kota dengan standar hidup tertinggi di Indonesia. Ukurannya adalah pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan, bukan sekadar harga makanan atau biaya kos.
Angkanya tinggi. Didominasi pengeluaran non-makanan, yakni perumahan, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan jasa. Di atas kertas, ini mencerminkan kesejahteraan. Namun di lapangan, cerita sering kali berbeda.
Bagi banyak warga Denpasar, terutama pekerja sektor informal, pekerja kreatif, jurnalis lepas, buruh pariwisata, hingga pekerja jasa, standar hidup tinggi tidak selalu berarti hidup layak. Upah Minimum Kota Denpasar sering kali tak sebanding dengan biaya sewa, transportasi, dan kebutuhan dasar lain.
Di sinilah paradoks itu bekerja. Kota disebut “mahal” bukan karena warganya kaya, tetapi karena harga hidup melaju lebih cepat daripada pendapatan rata-rata.
Persaingan hidup di Denpasar hari ini tidak lagi bersifat lokal. Arus migrasi yang masif membuat kota ini menjadi ruang temu banyak kepentingan. Pekerja datang dari berbagai daerah di Indonesia, mengadu nasib di sektor pariwisata, jasa, kreatif, hingga informal.
Ini bukan hal baru dalam sejarah Bali. Sejak lama, pulau ini terbuka. Namun intensitasnya kini jauh lebih tinggi. Persaingan kerja semakin ketat. Lapangan kerja tidak bertambah secepat jumlah pencari kerja.
Bagi orang Bali sendiri, kondisi ini sering terasa sebagai taluh apit batu versi modern. Di satu sisi, mereka harus bersaing di pasar kerja terbuka. Di sisi lain, mereka tetap memikul kewajiban adat, sosial, dan kultural yang tidak ringan—ngayah, upacara, kontribusi banjar, dan kewajiban keluarga besar.
Tekanan datang dari dua arah; ekonomi modern dan struktur sosial tradisional.
Budaya Bali tidak memandang persaingan secara frontal seperti dalam logika kapitalisme murni. Dalam nilai tradisional, hidup bukan soal saling mengalahkan, melainkan menjaga keseimbangan (rwa bhineda).
Ada pepatah lain yang sering diingat: “De ngaden awak bisa, depang anake ngadanin.” Jangan merasa paling bisa, biarkan orang lain menilai. Ini bukan ajakan pasrah, tetapi sikap rendah hati dalam persaingan.
Orang Bali juga mengenal strategi bertahan hidup yang lentur: memiliki lebih dari satu sumber penghasilan, bekerja sambil berdagang kecil-kecilan, atau memanfaatkan jaringan sosial banjar dan keluarga. Seperti Raka dengan toko buku onlinenya, banyak warga Denpasar hidup dari kombinasi pekerjaan formal dan informal.
Dalam kondisi taluh apit batu, yang diutamakan bukan melawan batu, tetapi mencari celah agar telur tidak pecah.
Antara Bertahan dan Bersyukur
Raka tahu hidupnya tidak ideal. Ia juga tahu Denpasar bukan kota yang ramah bagi semua orang. Namun ia memilih bertahan. Bukan karena tak punya pilihan, melainkan karena ia percaya hidup bukan hanya soal angka statistik.
Ia bersyukur masih bisa makan nasi jinggo, masih bisa membayar kos, masih bisa membeli buku, dan masih bisa menulis. Dalam bahasa Bali, ia sedang ngayah pada hidupnya sendiri—melakukan yang terbaik dalam keterbatasan.
Taluh apit batu bukan akhir dari segalanya. Dalam banyak kisah Bali, telur yang terjepit bisa saja pecah. Tapi bisa juga menetas, jika waktu dan keberuntungan berpihak.
Ketika Denpasar disebut sebagai kota dengan standar hidup tertinggi di Indonesia, penting untuk bertanya: standar hidup versi siapa? Statistik penting, tetapi kehidupan sehari-hari jauh lebih kompleks.
Bagi sebagian orang, Denpasar adalah kota peluang. Bagi sebagian lain, ia adalah ruang bertahan. Di antara keduanya, banyak yang hidup dalam kondisi taluh apit batu—terjepit, rapuh, namun belum menyerah.
Orang Bali sejak lama memahami bahwa hidup tidak selalu tentang menang. Kadang, hidup adalah soal tidak pecah, dan itu saja sudah merupakan sebuah keberhasilan. (*)
*Penulis adalah adalah jurnalis dan penulis yang tinggal di Denpasar. Buku terbarunya berjudul Di Beranda Kost, Gosip Kedengaran Lagi.